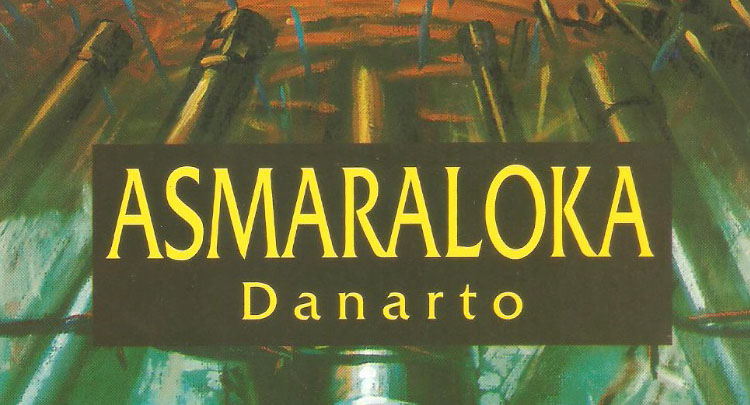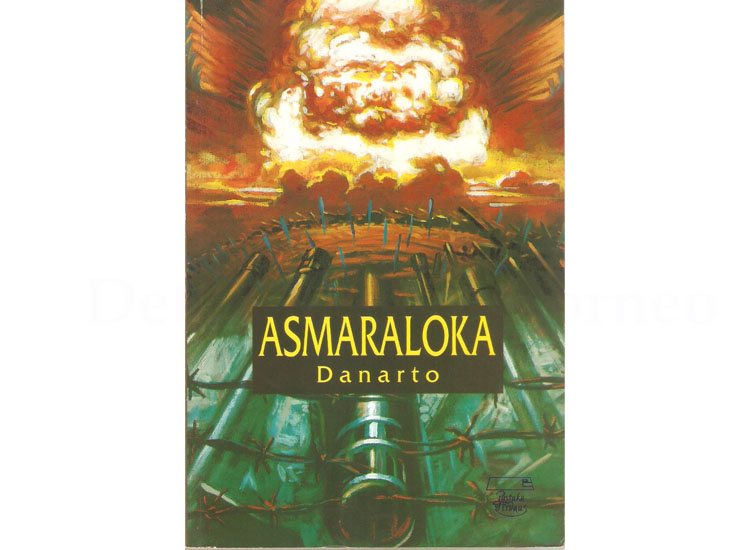| Resensator: Handoko Widagdo
Judul : Asmaraloka
Penulis : Danarto
Tahun Terbit : 1999
Peberbit : Pustaka Firdaus
Tebal : xi + 247 halaman
Danarto adalah Jawa. Orang Jawa adalah orang yang sudah paripurna dalam urusan relijiusitas. Sudah meneb. Orang Jawa bisa memeluk agama apa saja, tetapi tetap menggunakan tafsir Jawa dalam mencari Tuhan. Itulah sebabnya Danarto tak segan-segan mengajukan pendapat bahwa sebaiknya setiap orang memiliki agamanya sendiri.
Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konguchu, atau agama apapun adalah bendera. Masing-masing bisa mengibarkan bendera, tetapi dalam penghayatan mencari yang Esa tetap saja menggunakan agamanya sendiri-sendiri. Sangat indah apabila di mall-mall, di angkot, di bus, di kereta, di pasar orang saling sapa dan saling tanya: “Sudahkah engkau menemukan agamamu sendiri?”
Dalam novel ini Danarto berkisah tentang perang. Perang yang tidak jelas siapa lawan siapa kawan. Perang yang abadi. Perang yang tidak memiliki tujuan, atau yang bertujuan untuk melanjutkan perang. Perang yang sudah menjadi bahan konsumsi, layaknya sebuah pertandingan sepakbola. Siaran langsung sebuah perang adalah tontonan yang disukai. Bahkan tersedia layanan wisata perang dari garis depan.
Alur cerita dibangun dengan tokoh Arum, perempuan yang mengejar malaikat yang membawa jenazah suaminya, Busro. Dalam perjalanan mengejar mayat suaminya ini, Arum bertemu dengan Kyai Mahfud Muhammad dari Pondok Pesantren Waliyatul Rasuli. Arum yang kehilangan jejak malaikat dinasihati oleh Kyai Mahfud untuk menuju suatu tempat bernama parit berapi.
Pada waktu Arum berada di pondok Waliyatul Rasuli, dia diintip oleh seorang santri bernama Firdaus. Firdaus yang baru akil balik sangat tertarik dengan Arum. Cerita kemudian bersambung secara kronologis-magis mengikuti perjalanan Arum dan Firdaus di dunia peperangan. Sampai akhirnya Arum melahirkan anak kembar dari benih Busro suaminya – Ati dan Argo.
Dan perang itu adalah sejarah manusia. Apakah penciptaan manusia adalah sebuah kecelakaan? Apakah ini sebuah malapetaka? Sebab manusia telah menciptakan perang dengan segala alasannya. Beribu, bahkan berjuta manusia telah tewas sia-sia. Sementara bendera yang dijadikan pedoman untuk berperang terus-menerus berkibar.
Bendera Bulan Sabit milik pasukan Islam, bendera Salib milik pasukan Katholik, bendera Obor milik pasukan Protestan, Bendera Teratai milik pasukan Budha, Bendera Kamboja milik pasukan Hindu, Bendera Bintang Daun milik pasukan Yahudi, bendera Swastika milik pasukan Nazi, bendera Palu Arit milik pasukan Komunis, Bendera Cakra milik pasukan Kebatinan, bendera Hio milih pasukan Konghucu, bendera Kenanga milik pasukan Perempuan, bendera Rantai milik pasukan Manusia Kloning, bendera Angin milik pasukan Sufi dan bendera-bendera lain yang tetap berkibar sementara di bawahnya telah bergelimpangan mayat-mayat akibat perang.
Danarto, meminjam mulut Kyai Ababil Muhammad alias Kyai Kadung Ora dari Pesantren Gubaarullah. Kyai yang meyakini bahwa “dengan sendirinya kita adalah Tuhan, tak lain tak bukan” (manunggaling kawula-gusti?) menyampaikan bahwa satu-satunya jalan keluar bagi manusia adalah kalau setiap individu manusia memiliki agamanya sendiri (hal. 118-119). ”Inilah satu-satunya harapan bagi keselamatan umat manusia – umat kebinatangan. Setiap orang berhak punya agamanya sendiri menurut kemauannya sendiri. Setiap orang adalah hukum agama bagi dirinya sendiri. Setiap orang mendapatkan pencerahan dari pengertiannya sendiri tentang agama.” Dengan demikian setiap individu manusia dibebaskan untuk membuat tafsir terhadap kitab suci masing-masing untuk mencari tujuan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.
Dan Arum melahirkan anak kembar Ati dan Argo. Arum memutuskan untuk pulang ke kampung dan meninggalkan perang. Namun saat Ati dan Argo sudah dewasa mereka berdua pamit untuk berperang. Perang memang kodrat manusia.
Jadi kera tak perlu cemburu dengan evolusi manusia. Sebab terjadinya manusia adalah sebuah kecelakaan evolusi. Kecelakaan ini hanya bisa diselesaikan apabila setiap manusia menemukan agamanya sendiri.
Jika manusia berani berhubungan langsung dengan Sang Khalik. Dan agama-agama, ideologi-ideologi tersebut menjadi bendera saja. Bukan sesuatu yang diciptakan manusia untuk ditaati oleh manusia.
***
Bionarasi

Handoko Widagdo dilahirkan di Grobogan pada 25 Maret 1965. Pemulung dan pembaca buku. Menulis lebih dari 600 resensi buku. Sebagian resensi terbit di Harian Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Kompas.id, Koran Sindo, Komunitas Bambu; Menulis feature di The Jakarta Post dan Majalah Jade.
Menulis buku:
1. Penggerek Batang Padi
2. Anak Cino
3. Kalimantan Utara di Mata Saya.
Menulis buku bersama:
1. Indonesia Amnesia
2. #KamiJokowi
3. Aji “Chen” Bromokusumo – Politisi Tionghoa yang Menerobos Tradisi.